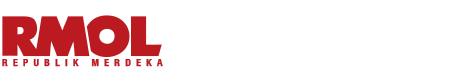- Wapres Maruf Amin Minta Polri Ungkap Motif Penembakan Kantor MUI
- Mensos: Perintah Presiden Jelas, Terorisme Dan Radikalisme Musuh Bersama
- Sosiaslisasi KUHP Baru Diperlukan
Baca Juga
Bahkan gelombang protes yang dilakukan dalam forum-forum akademis tak ayal jadi sasaran sabotase digital pihak-pihak yang kegerahan dengan aktivitas kritis rakyat sipil. Aneh memang, pasca Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kejahatan korupsi seolah mewabah menggerogoti nilai hakikat dari demokrasi itu sendiri.
Banyak diskusi akademis yang digagas oleh para pegiat anti korupsi mengkritisi bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah upaya menyingkirkan orang-orang pemberani yang ada dalam tubuh KPK. 75 orang pegawai lama KPK yang di dalamnya termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan tersingkir lewat sebuah tes wawasan kebangsaan yang pertanyaanya jauh dari nilai integritas juga nilai moral.
Melalui regulasi terbarunya KPK dilemahkan lewat keberadaan dewan pengawas, ada juga suatu kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Lewat mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK kehilangan independensinya sebagai lembaga yang seharusnya diberikan kekhususan karena korupsi merupakan extra ordinary crime.
Sampai disini kita memahami bahwa para pemimpin hari ini tidak benar-benar mewakili aspirasi dari publik melainkan mengakomodir kepentingan golongannya saja. Lantas apakah ada yang keliru dengan para pemimpin kita? Adakah benang merah antara kenyataan korupsi yang kini mewabah dengan hajat demokrasi yang telah terselenggara pada tahun 2019 dan 2020?
Parameter demokrasi dari segi kuantitas cenderung memiliki tren meningkat salah satunya ditandai oleh jumlah partisipasi masyarakat yang datang ke TPS. Namun demokrasi yang berkualitas bukan hanya menyoal angka pemilih yang bertambah namun harus dibarengi kualitas dari para pemilihnya.
Pemilih harus memiliki standar untuk memilih pemimpin yang paling berkualitas menilai trade record dan visi misinya. Idealnya penyelenggara Pemilu membuka data rapor merah catatan korupsi dalam CV calon pemimpin agar masyarakat dapat menilai secara utuh, tidak membeli kucing dalam karung.
Pemimpin yang berkualitas lahir dari kompetisi yang bersih, mengampanyekan perlawanan terhadap segala bentuk perilaku koruptif yang mungkin terjadi selama masa Pemilu atau Pilkada. Hal itu bisa berbentuk politik transaksional seperti mahar politik, jual beli suara dengan pemilih, suap menyuap dengan penyelenggara juga aparat penegak hukum.
Politik transaksional yang demikian membuat kandidat harus menyiapkan modal ekstra yang disuntikkan oleh para cukong dan di kemudian hari akan ada politik balas budi.
Upaya-upaya menghadirkan pemimpin yang bersih bukan hanya dari kualitas personal sang calon pemimpin dan komitmen Parpol saja melainkan harus dibarengi aturan main dalam Pemilu dan Pilkada yang tegas berkepastian dan berkeadilan.
Beberapa aturan yang abu-abu dapat menjadi celah yang dipergunakan pihak tertentu yang hanya peduli kalkulasi suara kemenangan dan menghiraukan kualitas dan reputasi dari demokrasi itu sendiri.
Misalnya saja dalam aturan larangan money politik yang hari ini belum cukup tajam menjangkau para aktor intelektual dalam kejahatan tersebut.
Dalam pidana dikenal penyertaan atau turut serta namun dalam kejahatan money politik aturan didesain kaku hingga sukar menjangkau aktor jahat yang sesungguhnya. Tak jarang masyarakat biasa yang tangannya dipinjam untuk bertransaksi jual beli suara lah yang malah terkena hukuman.
Selanjutnya abuse of power yang dilakukan oleh petahana baik ditingkat nasional maupun daerah-daerah juga tak mampu dijangkau oleh hukum. Misal dalam Pasal 71 UU Pilkada, semangat membatasi kekuasaan petahana semenjak enam bulan sebelum penetapan calon masih dinilai abu-abu karena frasa ‘merugikan paslon’ menggunakan subjek hukum yang absurd dalam keterpenuhan unsurnya.
Maka penulis beranggapan celah hukum yang terdapat dalam regulasi kepemiluan memiliki andil besar terhadap maraknya perbuatan koruptif dalam hajat demokrasi. Belum disempurnakannya regulasi kepemiluan berpotensi mempengaruhi Proses elektoral yang prematur dapat melahirkan pemimpin yang cenderung memiliki perilaku koruptif dalam menjalankan kepemimpinannya.
Lantas apakah celah hukum ini bisa diperbaiki dengan harapan dapat membentengi proses elektoral yang lebih berkualitas di masa mendatang? Penulis berharap lewat revisi UU Pemilu banyak pekerjaan rumah Demokrasi yang dapat dicicil agar segera diselesaikan. Namun harapan itu kandas karena RUU Pemilu ditarik dari Prolegnas.
Pengerjaan program legislasi hanya sekedar sesuai selera penguasa. Kebijakan yang mengarah pada upaya pelemahan pemberantasan korupsi dikerjakan dengan cepat, sementara urgensi RUU Pemilu dengan segala problematikanya berkaca dari Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dapat ditangguhkan karena harus berhitung kalkulator politik.
Dipermanenkannya lembaga KPU dan Bawaslu hingga jenjang kabupaten/kota tentu diharapkan memperkuat kesadaran berdemokrasi di akar rumput. Demokrasi yang substantif bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja namun juga peserta Pemilu dan Pilkada yaitu partai politik harus memiliki kesadaran yang sama.
Hari ini partai politik merupakan institusi terkuat yang dapat memegang kendali atas kebijakan pemerintah, maka reformasi di badan Parpol diperlukan untuk mengevaluasi setiap representasi kadernya.
Campur tangan kapitalisme dibalik kekuatan oligarki melanggengkan hasrat politiknya dinilai menjadi virus yang membuat korupsi mewabah belakangan. Formula tepat untuk memutus mata rantai nya amat perlu disiapkan menjadi payung hukum melalui regulasi kepemiluan yang progresif.
Komitmen anti korupsi harus bergema di penjuru negeri sehingga tercipta konsolidasi anti korupsi yang menjadi harapan bagi kemakmuran, keadilan di Negara Indonesia.
Firmawati
Divisi Hukum dan Advokasi Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Aktivis Nasyiatul Aisyiyah
- Anti-Vaksin, 12 Ribu Prajurit Angkatan Udara AS Terancam Dipecat
- Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI
- DPD Apresiasi Komitmen Qatar Lindungi TKI